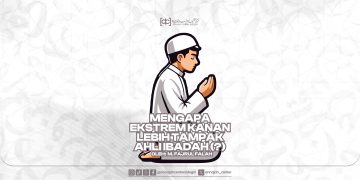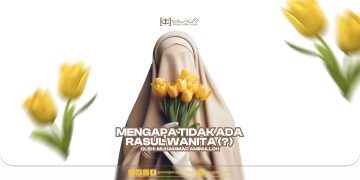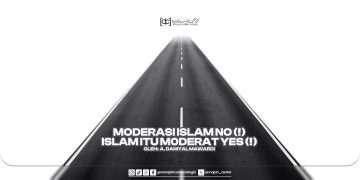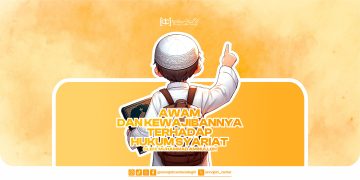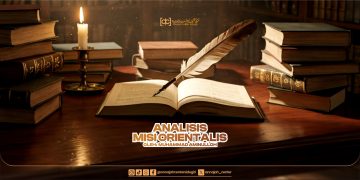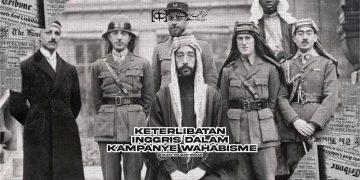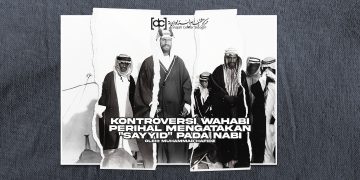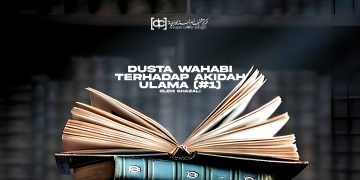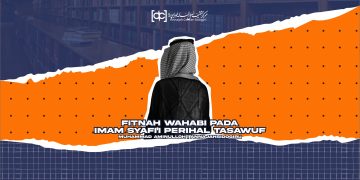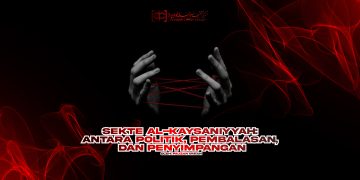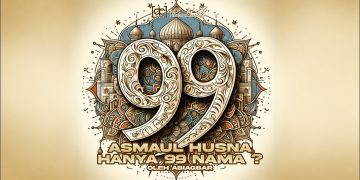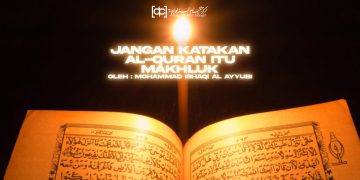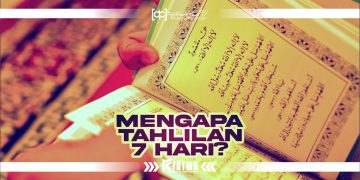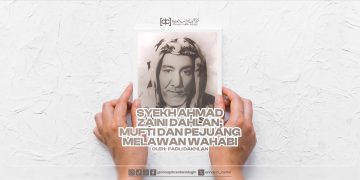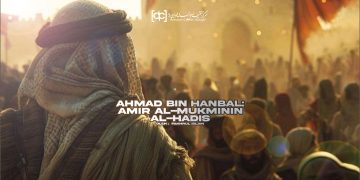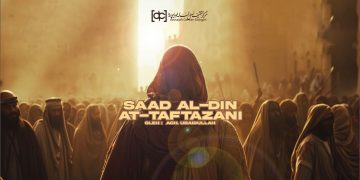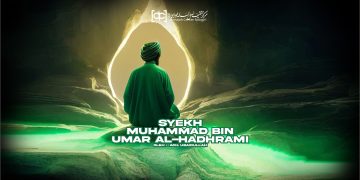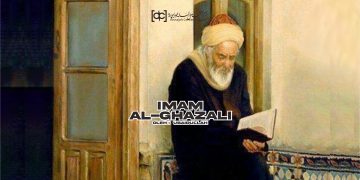Hari Sial Sebagai Latar Belakang Budaya
Sungguh disayangkan bahwa sebagian budaya dan tradisi yang ada di negeri kita tercinta ini mengandung keyakinan dan kepercayaan yang dapat mempengaruhi kemurnian akidah Islam bagi para pemeluknya. Salah satu yang umum kita jumpai di tengah-tengah masyarakat adalah kepercayaan mereka tentang hari sial. Dalam budaya Jawa, kepercayaan ini dikenal dengan istilah “dina ala”(hari buruk). Sedangkan untuk mengetahuinya, masyarakat kerap merujuk pada hasil perhitungan dalam primbon, yakni sistem penanggalan tradisional yang digunakan untuk menentukan baik-buruknya waktu dalam memulai atau melakukan suatu kegiatan.
Contohnya, mereka biasanya akan menghindari dan menunda untuk melakukan kegiatan atau hajatan tertentu pada hari Jumat Legi atau Selasa Kliwon, karena mereka meyakini hari-hari tersebut sebagai ‘hari naas’ atau hari sial untuk memulai suatu kegiatan besar seperti pernikahan dan acara lainnya.[1]
Jejak Serupa dalam Budaya Jahiliah
Menariknya, kepercayaan semacam ini bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban umat manusia. Fenomena di atas sebenarnya memiliki kemiripan dengan tradisi dan budaya di zaman Jahiliyah. Pada masa itu, orang Arab enggan melakukan atau memulai suatu kegiatan, terutama bepergian, jika bertepatan dengan hari sial (versi mereka). Namun bedanya, jika dasar konsep hari sial yang ada di masyarakat kita merujuk pada perhitungan dalam primbon, masyarakat Jahiliyah bertendensi pada kejadian tertentu yang mereka anggap dapat menunjukkan sial dan tidaknya nasib mereka. Biasanya, mereka mengambil isyarat dari arah terbang burung, jika burung terbang ke arah kanan mereka akan menganggap bahwa hari itu adalah hari yang baik dan beruntung, namun jika sebaliknya, mereka akan menunda atau membatalkan bepergiannya, karena menurut mereka hari itu sedang tidak bersahabat.[2]
Baca Juga; Syariat Islam Harus Dijalankan
Pandangan Islam: Kritik Al-Qur’an dan Hadis terhadap Tathayyur
Dalam Islam, menganggap sial atau merasa bernasib buruk karena suatu hal –seperti contoh di atas- disebut dengan istilah Thiyarah atau Tathayyur.[3] Islam melarang dengan keras praktik ini karena bertentangan dengan prinsip tawakal dan mencerminkan prasangka buruk kepada Allah ﷻ dan ketetapan-Nya. Ini menunjukkan bahwa hadirnya Islam sebagai korektor, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga menyentuh seluruh dimensi kehidupan dan sosial kemasyarakatan, termasuk tradisi dan budaya. Rasulullah ﷺ bersabda:
“الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ”
artinya: “Thiyarah adalah syirik, thiyarah adalah syirik -tiga kali-. Tidaklah di antara kita kecuali beranggapan seperti itu, akan tetapi Allah ﷻ menghilangkannya dengan tawakal.”[4](HR. Abu Dawud: 3411, Tirmidzi: 1539, Ibnu Majah: 3538)
Tidak hanya dalam hadis, Al-Qur’an juga mengabadikan praktik ini—yang juga merupakan perbuatan kaum-kaum terdahulu—dan memberikan kritik secara eksplisit dalam beberapa surah, di antaranya:
- Surah Al-A’raf: 131, tentang kaum fir’aun yang menyalahkan nabi Musa atas musibah yang menimpa mereka.
- Surah Yasin: 18–19, mengenai umat yang menganggap para rasul membawa kesialan.
- Surah An-Naml: 47, tentang kaum Tsamud yang menyalahkan nabi Shaleh atas bencana yang datang.
Banyaknya bunyi larangan Ini dalam Al-Qur’an maupun hadis, menunjukkan betapa seriusnya perhatian agama pada praktik tathayyur dan dampaknya terhadap akidah seorang Muslim.
Baca Juga; Keretakan Teori Evolusi
Anjuran Tafâul: Melangkah dengan Optimisme
Alih-alih mempercayai Tathayyur, Agama menganjurkan kita untuk bersikap optimis dan positif terhadap suatu hal (Tafâul). Sikap ini sangat disenangi oleh Rasulullah ﷺ karena mencerminkan husnu-zan kepada Allah ﷻ. Mengenai hal ini, al-Imam Ibn Majah meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah yang berbunyi:
كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ
“Rasulullah ﷺ menyukai tafaul yang baik dan membenci anggapan sial”
Sebagai penutup, penulis ingin mengingatkan bahwa fenomena apapun yang terjadi di sekitar kita, baik dalam kehidupan pribadi individu ataupun ruang lingkup sosial kemasyarakatan seperti tradisi dan budaya, haruslah kita saring terlebih dahulu mengikuti koridor yang telah ditetapkan oleh agama. Demikian ini agar tidak terjadi kesalahan fatal yang bersifat fundamental dalam akidah, tapi justru kita maklumi karena alasan lumrah dan sudah menjadi tradisi.
Wallahu a’lam bis-shawab…
Muhammad Asrori | Annajahsidogiri.id
[1]Suprianto Suwardi, Sumber Artikel berjudul ” Cara Mengetahui Hari Sial Menurut Primbon Jawa “, selengkapnya dengan link: https://portalkotamobagu.pikiran-rakyat.com/ramalan/pr-1774075828/cara-mengetahui-hari-sial-menurut-primbon-jawa?page=all dan https://kumparan.com/dukun-millennial
2ويَطَّيَّرُوا أَصْلُهُ يَتَطَيَّرُوا، وَهُوَ تَفَعُّلٌ، مُشْتَقٌّ مِنَ اسْمِ الطَّيْرِ، -إلى أن قال- . وَكَانَ الْعَرَبُ إِذَا خَرَجُوا فِي سَفَرٍ لِحَاجَةٍ، نَظَرُوا إِلَى مَا يُلَاقِيهِمْ أَوَّلَ سِيَرِهِمْ مِنْ طَائِرٍ، فَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ فِي مُرُورِهِ عَلَامَاتِ يُمْنٍ وَعَلَامَاتِ شُؤْمٍ، فَالَّذِي فِي طيرانه عَلامَة بِمن فِي اصْطِلَاحِهِمْ يُسَمُّونَهُ السَّانِحَ، وَهُوَ الَّذِي يَنْهَضُ فَيَطِيرُ مِنْ جِهَةِ الْيَمِينِ لِلسَّائِرِ وَالَّذِي عَلَامَتُهُ الشُّؤْمُ هُوَ الْبَارِحُ وَهُوَ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْيَسَارِ، وَإِذَا وَجَدَ السَّائِرُ طَيْرًا جَاثِمًا أَثَارَهُ لِيَنْظُرَ أَيَّ جِهَةٍ يَطِيرُ، وَتُسَمَّى تِلْكَ الْإِثَارَةُ زَجْرًا، فَمِنَ الطَّيْرِ مَيْمُون وَمِنْه مشؤوم
ص65 – كتاب تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير – سورة الأعراف الآيات إلى – المكتبة الشاملة
الرابط https://shamela.ws/book/9776/3349#p6 :
[3] والطيّرة: فَمَا يُتشاءم بِهِ؛ والفأل: فِيمَا يُسْتَحبّ.
ص271 – كتاب تهذيب اللغة – باب اللام والفاء – المكتبة الشاملة
dan (يطيروا) يتشاءموا (بموسى ومن معه) من المؤمنين به، وقد كانت العرب تتطير بأشياء من الطيور والحيوانات، ثم استعمل بعد ذلك في كل من تشاءم بشيء في قول جميع المفسرين، ومثل هذا قوله تعالى (وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك).
ص438 – كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن – – المكتبة الشاملة
الرابط:https://shamela.ws/book/7031/4467#p15
الرابط: https://shamela.ws/book/37458/2585#p4
[4] HR. Abu Dawud: 3411, Tirmidzi: 1539, Ibnu Majah: 3538