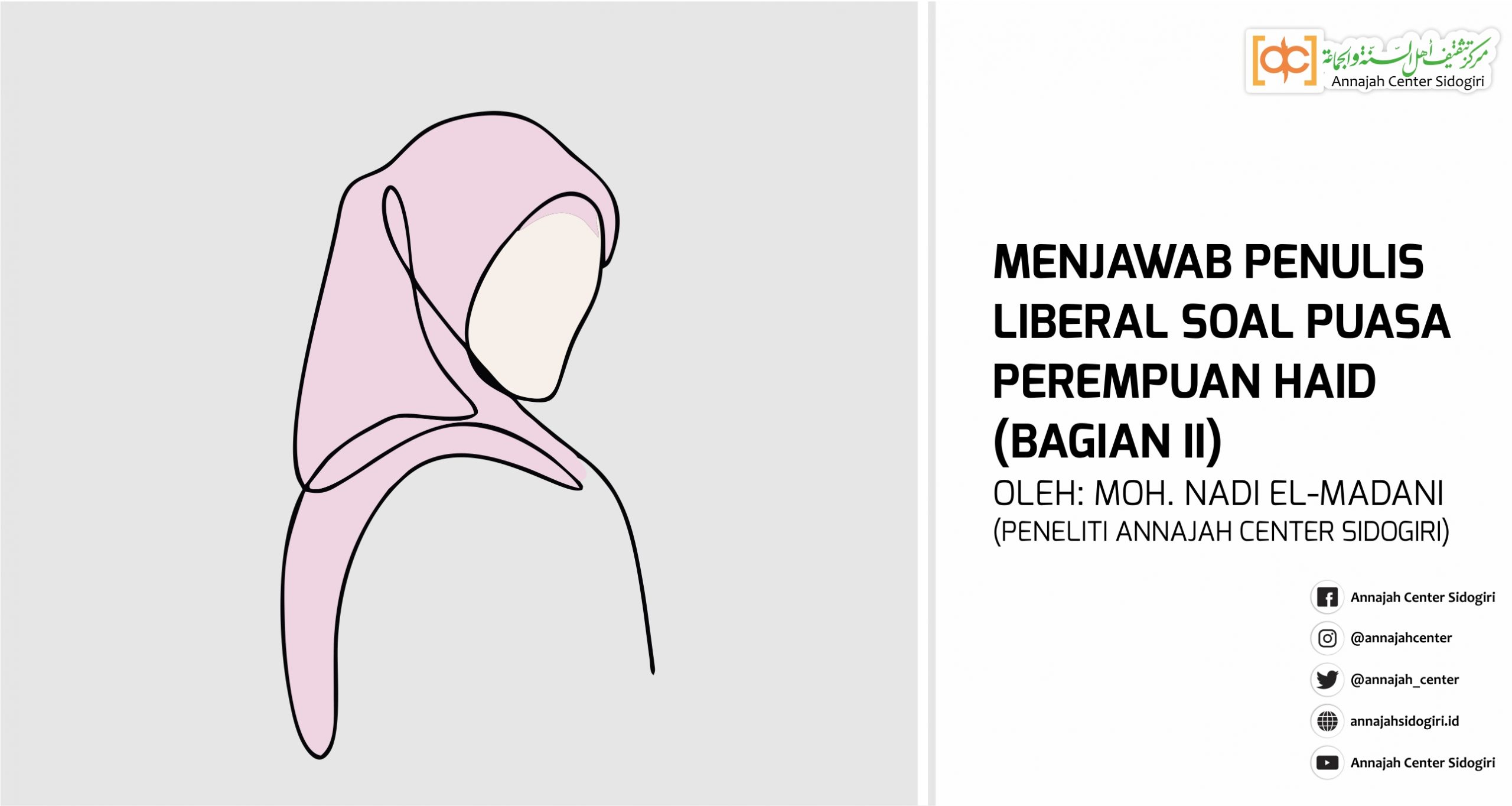Dari paparan yang telah penulis bentangkan pada bagian pertama, dapat kita ketahui bahwa konsensus ulama atas ketidakbolehan perempuan haid berpuasa memang tidak diekstrak dari al-Quran melainkan dari Sunnah Nabi. Sebagaimana maklum, sumber primer legislasi hukum Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya memiliki kedudukan yang setara sebagai sumber hukum, hanya berbeda secara hierarki. As-Sunnah dapat menjadi sumber independen dalam legislasi hukum Islam, ketika di dalam al-Quran tidak ditemukan dalil hukumnya. Salah satu contohnya adalah kasus hukum puasa perempuan haid di atas.
Nah, kaum liberalis tidak dapat membantah fakta as-Sunnah tersebut. Sebab itulah, mereka mencoba menafsirkan ulang hadis yang diriwayatkan dari Muadzah di atas. Mereka berpendapat bahwa sangat mungkin kata “تَقْضِيْ” dalam hadis di atas tidak bermakna “mengganti di luar waktu (qadhâ’)” melainkan “melaksanakan di dalam waktu (‘adâ’)”. Karena pada umumnya di dalam al-Qur’an, kata “قَضَى” bermakna melaksanakan di dalam waktunya. Salah satu contohnya adalah ayat berikut:
فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ
“Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu).” (QS an-Nisa’ [4]: 103)
Namun pertanyaannya, benarkah demikian? Lantas, apa alasan ulama memaknai kata “تَقْضِي” dalam hadis di atas dengan mengganti di luar waktunya? Dalam kitab Mu’jam al-Wasîth disebutkan bahwa kata “قَضَى” ada yang bermakna melaksanakan (adâ’) dan yang bermakna membayar (wafâ). Kemudian, makna melaksanakan mengandung dua kemungkinan, yaitu (1) melaksanakan di dalam waktu dan (2) melaksanakan di luar waktu. Para ulama memaknai kata “تَقْضِي” dengan makna kedua, yaitu membayar atau melaksanakan di luar waktunya. Dalilnya adalah hadis shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah berikut:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
Dari Siti Aisyah berkata: “Dahulu kami haid pada zaman Rasulullah. Setelah kami bersuci, beliau menyuruh kami mengqada puasa dan tidak mengqada shalat.”
Baca Juga: Menjawab Penulis Liberal Soal Puasa Perempuan Haid (Bagian I)
Al-Imam at-Tirmidzi mengomentari hadis tersebut:
هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اِخْتِلَافاً إِنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِيْ الصَّلَاةَ
“Hadis ini adalah hadis hasan. Para ahli ilmu mengamalkan hadis ini, kami tidak pernah mendapati perbedaan bahwa perempuan wajib mengqada puasa dan tidak wajib mengqada salat.” (Sunan al-Tirmidzi: 1/418).
Al-Imam an-Nawawi, dalam kitab Syarh Shahîh Muslim (1/26), menjelaskan bahwa alasan perempuan haid hanya wajib mengganti puasa dan tidak wajib mengganti salat adalah karena salat banyak dan berulang-ulang sehingga perempuan akan sangat kesulitan untuk menggantinya. Berbeda dengan puasa, yang hanya dilakukan satu bulan dalam setahun. Di tambah, bisa saja haidnya hanya sebentar, dua hari atau tiga hari.
Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa kata “تَقْضِيْ” dalam hadis di atas bermakna melaksanakan di dalam waktunya. Pendapat tersebut sama sekali tidak memiliki dasar, hanya igauan belaka, dan jelas telah menerabas konsensus ulama.
Di samping itu, jika memaksa memaknai kata “تَقْضِيْ” dengan melaksanakan di dalam waktunya, berarti perempuan haid wajib mengqada salatnya? Bukankah hal itu akan menyulitkan perempuan? Bayangkan jika haidnya sampai 15 hari? Dan bukankah karakteristik agama Islam itu mudah? Duh! Bisa-bisa kaum liberalis akan merevisi banyak hal dalam agama demi meng-cover kegenitan berpikir mereka. Bahaya!
Moh. Nadi el-Madani | Peneliti Annajah Center Sidogiri