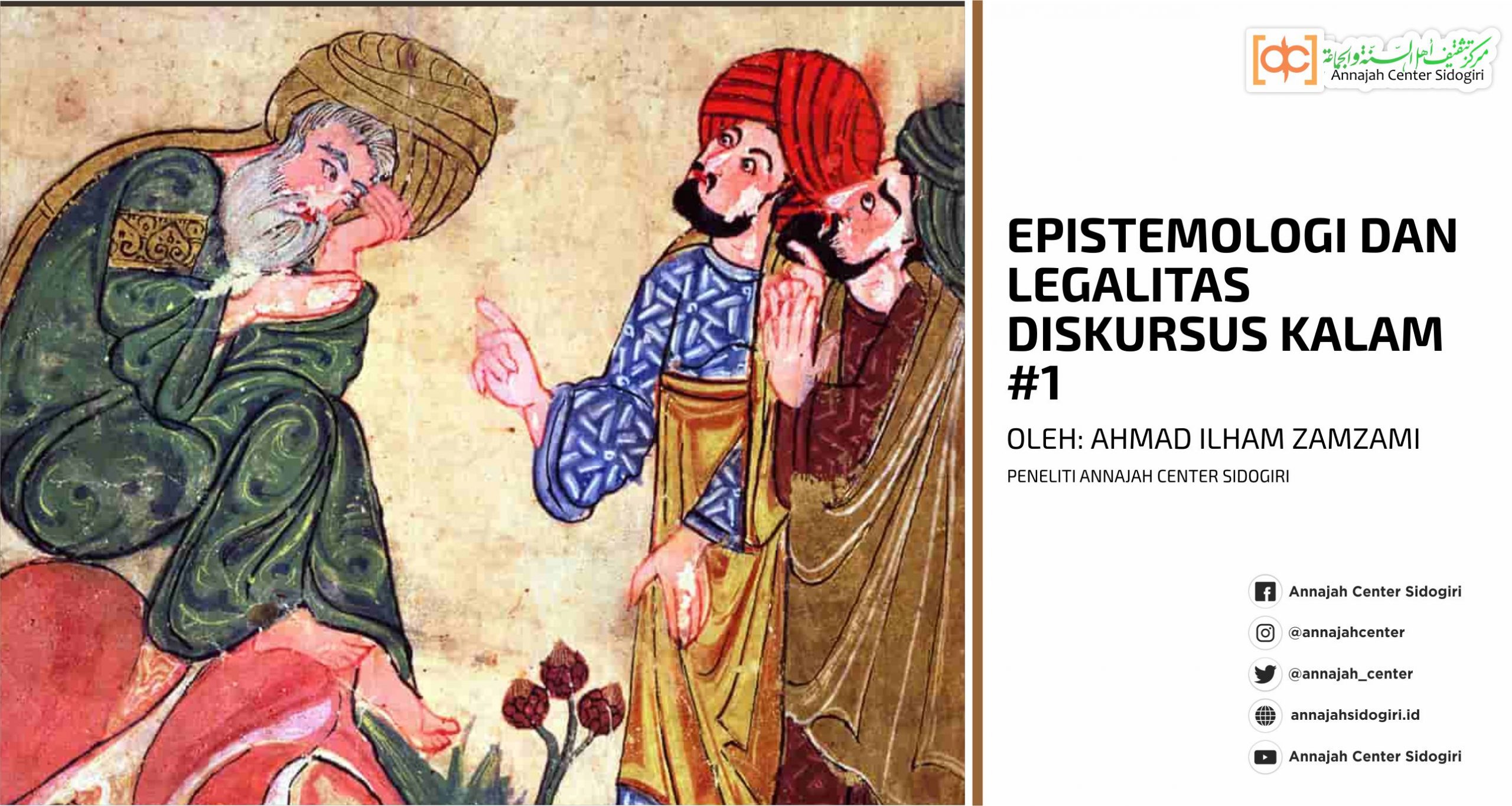Pada awal kemunculannya sebagai diskursus keilmuan, ilmu ini dideskripsikan berbeda-beda oleh para ulama. Sebagian besar mereka menyebutnya dengan deskripsi ekstern (ta’rîf rasm), sesuai dengan tinjauan yang berhubungan dengan kalam. Seperti Imam Abu Hanifah (w. 767) yang menakrifkannya dengan, “Ketahuilah bahwa ilmu fikih dalam usuludin itu lebih utama daripada fikih (yang berupa) hukum furu’… Dan fikih (sendiri) adalah mengetahuinya seseorang terhadap suatu keyakinan dan perbuatan yang diperbolehkan dan yang diwajibkan baginya… Apa yang berhubungan dengan keyakinan adalah fikih yang agung, dan yang berkaitan dengan perbuatan ialah fikih (saja)”. Dalam takrif ini, Abu Hanifah lebih menjelentrehkan perbedaan objek kajian dari fikih akbar dan fikih furuk, serta keunggulannya fikih akbar dari sisi ulasannya yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan. Dari situ terlihat, bahwa pioner mazhab Hanafi ini, masih belum menyentuh deskrispi limitatif (ta’rîf haddî) ilmu kalam.
Baca Juga: Mengurai Perbedaan Filsafat dan Ilmu Kalam
Model takrif yang sama juga diterapkan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H), di dalam al-Munqizh min al-Dlalâl-nya dia mengelaborasi dengan, “…Sesungguhnya yang dituntut (dalam kalam) ialah menjaga akidah Ahlusunah dari agitasi kaum bid’ah… Ketika reproduksi kalam (yang keliru mulai) marak dan banyak yang membincangkannya, maka para mutakalim tergerak untuk membela Sunah dengan meneliti esensi segala perkara dan mereka mengobservasi substansi (materi), aksidental, dan predikat keduanya…”.
Al-Ghazali di sini, lebih menganalisa konten kalam sebagai konservator akidah dari segala bentuk syubhat yang ditujukan pada agama. Dan juga term “kalam” hanya ditujukan pada kelompok Ahlusunah saja, yang semestinya juga bisa diarahkan kepada kelompok di luar Ahlusunah. Sehingga bentuk takrif darinya masih belum sesuai kriteria takrif haddî, yang tersusun dari genus universal (jins kullî) dan sifat diferensial (fashl).
Baca Juga: Hermeneutika Versus Tasfir al-Quran
Barulah di kurun ketujuh hingga kesembilan hijriah, teolog Islam mulai menakrifkan kalam berdasarkan deskripsi limitatif. Di antaranya Imam ‘Adudlin Abdurrahman al-Igi (w. 756 H), dia mendiskripsikannya dengan, “Kalam ialah (sebuah) pengetahuan yang senantiasa mampu mengafirmasi doktrin-doktrin agama dengan menghadirkan argumentasinya dan menepis syubhat atasnya”. Kemudian di dalam at-Ta’rîfât-nya, Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani (w. 816 H) menambahkannya dengan tema permasalahan yang dikaji di dalamnya, “Kalam yaitu (sebuah) pengetahuan yang di dalamnya membahas tentang Zat dan sifatnya Allah Swt, serta hal-ihwal sesuatu yang mungkin sejak awal kemunculan dan dibangkitkannya dengan bertedensi pada prinsip keislaman”.
Untuk menyempurnakan defenisi ini, seorang tokoh filologi dan teologi Islam dari al-Azhar, Prof. Dr. Hasan Mahmud Abdul Lathif asy-Syafi’i menyatakan, “Sesunguhnya kalam adalah (sebuah) pengetahuan yang didalamnya mengkaji hukum syariat (mengenai) keyakinan, yang bersinggungan dengan teologi, prophetisme, dan hal-hal gaib, demi membuktikan kebenaran dan menolak syubhat atasnya”.
Dari semua definisi barusan, kesimpulan yang dapat diambil bahwa terbentuknya ilmu kalam didasari atas intensitas dalam menjaga kemurnian ideologi Islam, dari segenap kerancuan paradigma dan ideologi yang menyimpang. Sayangnya meski telah diketahui aposteriori kalam, streotip yang disematkan padanya masih santer didengar dari golongan puritan dan fundamentalis.
Ahmad Ilham Zamzami | Peneliti Annajah Center Sidogiri, Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Usuludin, Dept. Akidah & Filsafat, Universitas Al-Azhar, Mesir dan Direktur Kajian Teologi PCINU Mesir