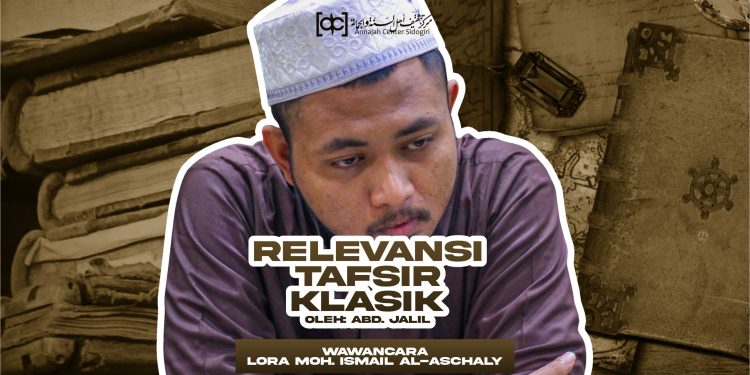Ilmu tafsir adalah fan penting dalam studi Islam. Ia terus berkembang dari masa ke masa, sehingga lahirlah banyak ragam metode yang dipakai ulama dalam menafsiri al-Qur’an. Namun, akhir-akhir ini muncul sebuah persoalan ketika relevansi tafsir yang dipakai ulama klasik mulai dipertanyakan. Mereka anggap tafsir klasik tersebut tidak mampu menjawab tantangan zaman. Seperti contoh, ketika menafsirkan ayat “Innad-Dîna ‘indallâhil-Islâm, Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.” (QS. Ali Imran [3]: 19). Ayat tersebut oleh Ibnu Katsir dan al-Qurtubi ditafsiri sebagai sebuah legitimasi untuk menafikan eksistensi agama lain.
Penafsiran seperti itu, menurut sebagian kalangan, tidaklah relevan untuk zaman sekarang, sebab bisa berpotensi adanya upaya pemaksaan kepada seseorang untuk memeluk Islam, dan jelas bertentangan dengan nas sharih yang memberi kebebasan untuk beragama (freedom of religion or belief). Terlebih jika dihubungkan dengan konteks zaman di era multikultural, yang mengharuskan masing-masing kita untuk bisa menghargai perbedaan kultur, tradisi, dan agama, dan tidak saling memaksakan kehendak, apalagi melakukan kekerasan atas nama agama. Masih banyak lagi contoh-contoh tafsiran ulama salaf yang mereka anggap tidak cocok untuk diterapakan saat ini.
Namun, di lain sisi mereka juga menawarkan solusi untuk masalah tersebut, yaitu pengaplikasian hermeneutika sebagai ganti dalam memahami al-Qur’an. Sayangnya, bukan solusi yang didapat melainkan perusakan ajaran Islam hingga akar-akarnya. Seperti kasus Abu Zayd Nasr dengan kesimpulannya bahwa al-Qur’an bukan sebagai kalam Allah tapi produk budaya (muntaj tsaqafi).
Untuk menanggapi fonomena ini, berikut pemaparan K.H. Muhammad Ismail Aschaly, ulama muda Madura yang juga keturunan Syaikhona Kholil Bangkalan, ketika diwawancarai oleh Abd. Jalil dari redaksi AnnajahSidogiri.id.
Metode ulama dalam menafsiri al-Qur’an dari waktu ke waktu?
Pertama, mungkin sebagai mukadimah, kita sebagai peneliti tafsir al-Qur’an, dan tentu bukan hanya sekadar peneliti, sebagai umat Islam mesti memiliki keyakinan kuat bahwa kita adalah pecinta al-Qur’an. Kita harus memiliki hubungan dengan al-Qur’an ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh ulama selama kurun waktu 1440 tahun, yaitu dengan cara yang biasa disebut dengan kata isnad atau sanad. Dikatakan oleh para ulama al-Isnâdu minad-dîn laulal-isnâd la qâla man syaa wa qâla man syâa (Sanad itu merupakan bagian dari Agama. Tanpanya, bisa jadi seseorang akan berfatwa seenaknya). Jadi, untuk berinteraksi dengan al-Qur’an kita harus memiliki sanad yang jelas. Baik sanad mengaji atau sanad memahami al-Qur’an.
Sanad yang dimaksud adalah sanad pemahaman yang sama sepeti cara pemahaman guru-guru kita sampai para mufasir di zaman klasik. Dengan sanad ilmiah atau pemahaman ini kita bisa dengan mudah memahami apa yang mereka maksudkan, sehingga jika kita memiliki sanad, kita akan temukan banyak sekali ulama dulu yang pendapatnya berbeda dengan ulama yang lebih klasik. Ulama murid yang berbeda dengan gurunya. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki sanad yang jelas dengan gurunya, kemudian, selain itu, ia juga memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki gurunya itu, sehingga ia bisa mengoreksi sebagian cara penafsiran gurunya itu. Lalu ia memiliki murid dan muridnya juga memiliki murid, begitu seterusnya. Dari situ terciptalah banyak cara atau metode-metode dalam memahami al-Qur’an yang begitu beragam.
Namun, untuk menjadikan ini sebagai cara kita untuk memahmi al-Qur’an tetap membutuhkan sanad yang jelas kepada seorang guru, seorang mufasir, dan begitu seterusnya. Jadi, berangkat dari situ, misalnya, tadi kita menemukan ayat innad-dina indalllahil Islam. Ibn katsir, Imam al-Qurtubi dan lain-lain mereka mengatakan yang dimaksud Islam ini adalah ya, agama Islam itu, sehingga selain Islam tidak indallah.
Nah, mereka mengatakan seperti itu, tentu yang pertama adalah karena sanad. Kedua adalah karena melihat siyaqul kalam pada ayat tersebut. Karena pada ayat selanjutnya, yaitu wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba’di ma jaahumul ilmu baghyan baynahum. Nah, ahlul kitab bisa ikhtilaf seperti itu karena mereka pernah didatangi satu ilmu yang pasti, kemudian mereka baghyan, mereka lacut, dengki, dan tidak jelas. Akhirnya, apa yang mereka (para ulama) lakukan sebenarnya masih cocok dengan siyaqul kalam pada ayat tersebut. Jadi, tidak bisa satu statement Ibn Katsir atau Imam al-Qurtubi dan para mufasir klasik yang lain, itu kemudian kita comot untuk menjelaskan tentang hal lain. Karena sebenarnya masih banyak hal-hal yang relevan milik ulama klasik, cuma kita yang salah dalam penempatannya.
bersambung….
Abd Jalil | Annajahsidogiri.id