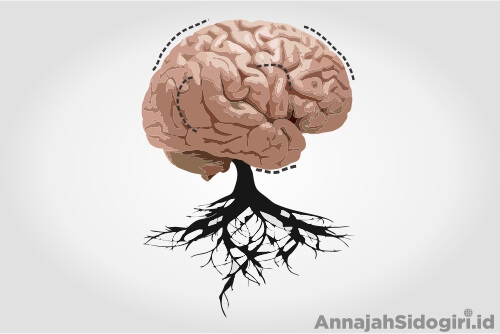Sejarah Sekte Muktazilah
Muktazilah secara bahasa berarti orang-orang yang mengasingkan diri. Menurut Syekh Zahid al-Kautsari mengutip pendapat Abul-Hasan ath-Thara’ifi (Lihat pengantar kitab: Tabyinul-Kidzb al-Muftari fi Ma Nusiba ilal-Imam Abil-hasan al-Asy’ari: 19) bahwa cikal-bakal Muktazilah berawal dari barisan setia (Syi’ah) Imam Ali bin Abi Thalib t yang mengasingkan diri dari perpolitikan Islam. Beberapa tahun kemudian, semenjak tapuk kekhilafahan Islam diserahkan oleh Khalifah al-Hasan bin Ali t kepada Sayidina Mu’awiyah bin Abi Sufyan t, banyak masyarakat Muslim yang berusaha fokus hanya mengaji dan beribadah kepada Allah I di masjid- masjid, para pelakunya adalah Abu Hasyim Abdullah dan al-Hasan yang keduanya merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Hanafiyah. Dari sini secara nama, mulai muncul istilah I’tizal (abstein) dalam berpolitik praktis. Mereka berkata: “Kami ingin menyibukkan diri dengan mengaji dan beribadah”.
Namun belakangan, kelompok ini bukan hanya mengasingkan diri dari kancah politik saja namun lebih kepada I’tizal dalam hal akidah. Mayoritas ulama mengatakan, pelopor pertama Muktazilah sebagai doktrin sekte agama dalam khazanah pemikiran Islam adalah Washil bin ‘Atha’ (w. 131 H). Awalnya ia adalah santri aktif al-Imam al-Hasan al-Bahsri (w. 110 H) yang pada akhirnya justru ia memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya dalam persoalan status pelaku dosa besar. Menurut Washil, pelaku dosa besar tidak berstatus Mukmin ataupun Kafir, ia berstatus abu-abu (al-manzilah baina manzilataini). Semenjak itulah, Washil melakukan I’tizal (mengasingkan diri) dari majelis gurunya, Hasan al-Bahsri, dan membuat majelis-nya sendiri. Dari sini kemudian pemikiran Muktazilah mulai berkembang, terhitung sejak era Dinasti Umawiyah dan baru menemukan jati dirinya sebagai ideologi resmi negara pada masa Dinasti Abbasiyah. (Lihat: Tarikhul-Madzahib al-Islamiyah: 118-119)
Baca Juga: Pandangan dan Kritik Terhadap Muktazilah
Seiring kemunculannya, konsep ideologi Muktazilah mulai dibangun. Menurut Dr. Muhamad Sa’id Ramadhan al-Buthi (1434 H/2013 M) mereka merumuskan lima ushulul-aqaid yang dipelopori oleh para tokoh berikut:
- Abu ‘Ali Muhammad bin ‘Abdul-Wahhab al-Jubba’i (302 H)
- Washil bin ‘Atha’
- ‘Amr bin ‘Ubaid (143 H)
- Bisyr bin Sa’id
- Bisyr bin al-Mu’tamir (226 H)
- Abul-Hudzail al-‘Allaf (135-225 H)
- Abu Bakar bin Kaisan al-Asham
- Ibrahim an-Nidzam (231 H)
Namun demikian, dalam tubuh Muktazilah juga terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat ”yang mereka mengkafirkan satu sama lain,” kata Syekh Abdul-Qahir al-Baghdadi (w. 429 H).
Lima Ushulul-‘Aqaid yang sekaligus menjadi syarat seorang disebut sebagai Mu’tazili itu adalah sebagai berikut:
1- At-Tauhid
Adalah ajaran paling mendasar bagi kelompok ini. Yang dimaksudkan dengan istilah at-Tauhid ini adalah tiga hal berikut;
Pertama, menafikan sifat-sifat Ma’ani bagi Allah I yang diyakini keberadaan-nya menurut penganut Ahlusunah Asya’irah. Yaitu Sama’ (Mendengar), Bashar (Melihat), Qudrat (Mampu), Iradah (Keinginan), ‘Ilmu (Mengetahui), Kalam (Berbicara), Hayat (Hidup). Namun di sisi lain, meyakini bahwa Allah I adalah Zat Yang Maha Mendengar (Sami’), Maha Melihat (Bashir), Maha Mengetahui (‘Alim), Maha Kuasa (Qadir), Maha Berkehendak (Murid), Maha Hidup (Hayyun) dan Maha Berbicara (Mutakallim). Maksudnya adalah Allah Maha Mengetahui (‘Alim)tanpa harus memiliki sifat Tahu (al-‘Ilmu) begitu seterusnya.
Demikian ini menurut mereka, apabila Allah I memiliki sifat Ma’ani maka Allah I harus juga memiliki banyak sifat Qidam lain (sifat tidak ada awalnya) selain Allah I. Dan ini akan menafikan keesaan (Tauhid) Allah I. Sebab akan ada yang Qidam selain Allah I.
Menjawab hal ini, dua poin berikut akan memberikan penjelasan akan kekeliruan Muktazilah, 1) secara logika dan nalar akal, sifat tidak akan ada tanpa ada zat. Ketika kita mengatakan bahwa Allah I memiliki sifat Tahu maka di saat yang sama kita juga harus mengatakan bahwa Allah I Maha Mengetahui. Ini tidak bisa dipisahkan. 2) dalam al-Quran, Allah sendiri menegaskan bahwa Dia memiliki sifat al-‘Ilmu dan al-Qudrat. Berikut salah satu cuplikan ayatnya,
{وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255]
…Tidak ada satupun yang dapat mengetahui ilmu-Nya kecuali apabila Dia memberitahukannya..
{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً } [فصلت: 15]
…Tidakkah mereka (kaum ‘Ad) melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih kuat daripada mereka..
Apabila sudah demikian, persoalan Muktazilah dapat terselesaikan dan terbantahkan. Ternyata, al-Quran sendiri yang menyatakan keberadaan sifat Ma’ani bagi Allah I.
Kedua, menafikan kemungkinan Allah I bisa dilihat kelak di Hari Kiamat. Menurut Muktazilah, apabila Allah bisa dilihat maka secara otomatis Dia bertempat dan ber-jisim sebagaimana lazimnya makhluk. Dan yang demikian ini menghilang sifat keesaan (Tauhid) Allah I. Sebab Allah akan sama dengan makhluk-Nya; bertempat dan berjisim.
Namun hal ini terbantahkan dengan nash al-Quran, bahwa kaum mukmin akan melihat Allah I kelak di Hari Kiamat.
{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) } [القيامة: 22 – 24]
“wajah-wajah kala itu berseri-seri, kepada Tuhan-nya mereka melihat.”
Sebagaimana kelak kaum kafir akan ditutupi untuk melihat Allah I.
{كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15)} [المطففين: 15]
“Sungguh mereka (orang-orang kafir) akan terhalang untuk melihat Allah.”
Ketiga, berasumsi bahwa Kalamullah adalah makhluk. Dengan ini, Muktazilah berkeyakinan bahwa al-Quran yang merupakan kalam ilahi bukan sifat Allah yang Qadim. Sebenarnya pembahasan ini berawal dari akidah mereka yang tidak meyakini keberadaan sifat Ma’ani yang sudah kami paparkan di muka. Hanya saja persoalan ini melahirkan peristiwa bersejarah yang oleh para ulama disebut Mihnatul-Quran, sejarah di mana para ulama Ahlusunah harus mengakui kemakhlukan al-Quran pada masa Dinasti Abbasiyah yang berideologi Muktazilah. (Lihat diskusi selengkapnya di ad-Difa’ ‘An Ahlissunnah wal Jamaah hal. 05)
Bersambung….
Fahim Abdoellah/ Annajahsidogiri.id