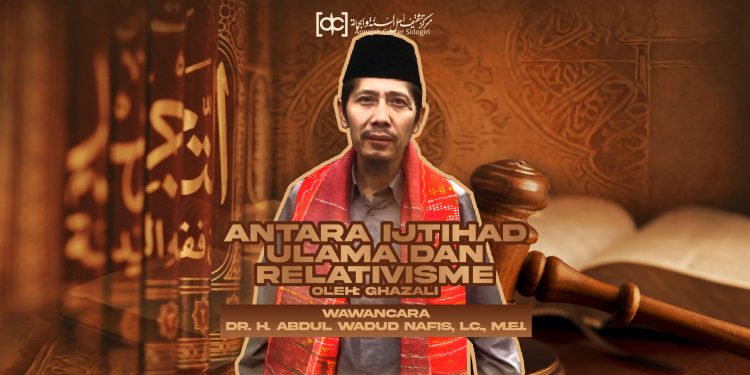Seringkali terdapat kesalahpahaman dalam memandang ijtihad para ulama. Ada yang mengatakan, “bila para ulama boleh berijtihad dan menggali hukum langsung dari Al-Qur’an dan hadis, mengapa kita tidak? Kan sama-sama bertumpu pada kitab dan sunah?” Sehingga dari pemikiran yang semacam itu, banyak yang membuahkan pendapat baru dalam hukum-hukum syariat yang menyalahi pendapat-pendapat ulama sebelumnya, bahkan menyalahi pendapat yang telah muktamad. Dari sini kemudian mereka berbangga-bangga atas pendapatnya yang dianggap sendiri sebagai pendapat yang segar, bahkan mengakui diri bahwa telah melakukan gerakan modernisme dalam Islam. Nah, apakah yang demikian itu dapat dibenarkan dalam prespektif Ahlusunah wal-Jamaah? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita simak hasil wawancara Ghazali dariAnnajahsidogiri.id kepada Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I. selaku dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beberapa waktu yang lalu.
Bagaimana pandangan Kiai terkait ijtihad para ulama?
Ijtihad itu sederhananya merupakan usaha seorang mujtahid untuk mencapai hukum-hukum syarak. Tentu, mereka bertumpu pada Al-Qur’an dan hadis. Namun dalam menggali hukum pada kedua kompenen inti tersebut, para mujtahid tidak asal-asalan. Penuh kehati-hatian dalam menggali hukum.
Oleh karenanya, dalam kitab-kitab Fikih, ulama memberi persyaratan yang sangat ketat bagi seseorang yang hendak berijtihad dan menjadi mujtahid. Kisaran 14 syarat yang ulama paparkan, di antaranya adalah harus memiliki akidah atau iman yang benar dan sahih, menguasai ilmu bahasa, dan lain-lain.
Ada yang berpandangan bahwa ijtihad langsung pada Al-Qur’an dan hadis boleh dilakukan siapa saja. Menurut Kiai?
Tidak bisa begitu. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tingkatan manusia dalam memahami hukum-hukum syariat, menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Ushûlul-Fiqhi al-Islâmy, bermacam-macam. Pertama, tingkat mujtahid mutlak. Ini tingkatan tertinggi. Ia harus paham betul segala macam bidang ilmu keagamaan. Pun, harus hafal Al-Qur’an, hadis, dan kriteria-kriterianya (meliputi sahih, daif, dan semacamnya), juga mendalam ilmu kebahasaannya yang meliputi ilmu Nahwu, Sharaf, dan Balagah, serta tak boleh terpaku pada suatu mazhab. Selain itu, ia juga mempunyai metode istinbâthul-ahkâm sendiri. Demikian ini semisal para imam mazhab yang empat; Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhmmad bin Idris asy-Syafii, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Kedua, tingkat mujtahid mazhab. Kemampuan orang yang ada pada tingkatan ini hampir sama dengan tingkatan mujtahid mutlak. Hanya saja, ia tidak memiliki metode istinbâthul-ahkâm sendiri, melainkan bersandar kepada metode imam mujtahid tertentu. Semisal Imam Nawawi yang metode istinbâth-nya. Ketiga adalah tingakatan mufti. Ia memiliki pemahaman agama yang terbilang banyak, namun belum sampai pada tingkatan kebolehan berijtihad, melainkan hanya sekadar mentarjih. Keilmuannya sudah mendekati tingkat mujtahid, namun tidak memiliki kemampuan berijtihad. Kemampuannya hanya sekadar memilih pendapat-pendapat ulama yang lebih unggul dengan menganalisis dalil-dalil ulama mujtahid.
Baca juga; Ijtihad Para Mujtahid Sekadar Opini ?
Keempat, muqallid. Seorang muqallid itu menguasai pada hukum dan juga paham pada dalil-dalilnya, hanya saja tak seluas tingkatan mufti. Kelima adalah awam. Syekh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa orang awam adalah orang yang paham hukum namun tak memahami dalilnya sama sekali.
Nah, ini dia tingkatan orang dalam memahami agama sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Ushûlul-Fiqhi al-Islâmy. Namun sebuah keanehan terjadi sekarang. Ada orang yang tidak paham sama sekali dalil, bahkan tak paham hukum. Tingkatannya dalam memahami agama, lebih rendah ketimbang tingkatan awam. Namun sayangnya, ia memosisikan dirinya sekelas mujtahid mutlak layaknya Imam Syafii. Tentu ini salah. Sebab bisa jadi, keputusan-keputusannya nanti malah bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah disepakati para ulama, bahkan bertentangan dengan hukum Al-Qur’an dan hadis itu sendiri.
Namun perbedaan pandang antara ulama, semisal Imam Syafii dengan Imam Malik, Imam Hanbali dengan Imam Abu Hanifah, seakan menunjukkan agama itu relativ dan siapapun berhak mengotak-atik.
Ya tidak seperti itu. Kalau perbedaan furuiyyah, selagi tidak menyalahi konsensus ulama, ya boleh-boleh saja. Sebagaimana yang sudah terjadi di antara ulama-ulama kita. Namun kalau pembahasannya ushûluddîn, tentu ini tidak boleh. Sifatnya absolut dan tak boleh diotak-atik.
Saya setuju terhadap pernyataan relativisme asal dengan makna yang positif dan hal ini sudah banyak terjadi sejak zaman salaf. Misal terkait masalah qunut antara Imam Syafii dan Imam Ahmad. Imam Syafii memandang hadis yang membahas qunut itu sanadnya sahih. Sedang Imam Ahmad memandang hadis tersebut daif sehingga beliau menghukumi qunut itu tidak sunah.
Ghazali | Annajahsidogiri.id