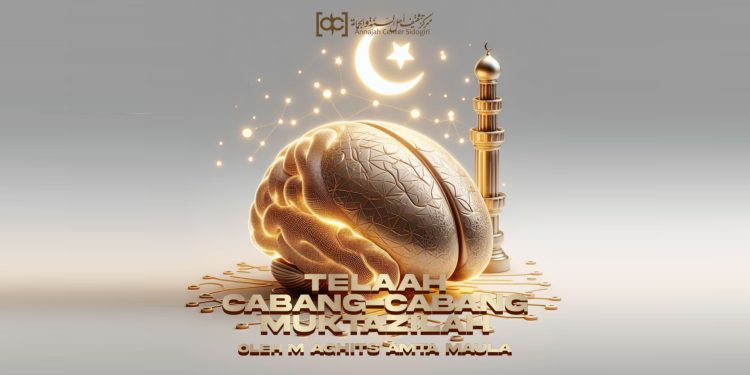Telah tercatat rapi dalam sejarah, bahwa Muktazilah merupakan salah satu sekte penyebar paham sesat yang telah mengotori khazanah keilmuan Islam. Muktazilah juga merupakan satu sekte yang bisa dibilang cukup besar dan mempunyai banyak cabang, yang mana dari semua cabang tersebut mempunyai satu tujuan, yakni merusak tatanan akidah dan syariat yang telah dirumuskan oleh para ulama Ahlussunah wal jamaah. Oleh karenanya, kajian kali ini akan membahas tentang cabang-cabang sekte Muktazilah.
1- Al-wāshîliyah
Aliran yang dipimpin oleh Abi Hudzaifa Washil bin Atha’ atau yang biasa dijuluki dengan al-Ghazzal (الغزال) yang artinya adalah Rusa, julukan ini disematkan kepada Washil bin Atha’ karena dia biasa mengikuti kijang untuk mengidentifikasi wanita suci dan memberikan sedekah kepada mereka[1]. Washil bin atha` juga merupakan salah satu murid dari Imam Hasan al-Bashri. Dari Imam Hasan al-Basri ini Washil bin Atha` banyak mengkaji berbagai ilmu mulai dari ilmu kalam, mantiq, ushul fiqh, fiqh, serta masih banyak lagi. Akan tetapi pada akhirnya, dia menyimpang dari apa yang diajarkan oleh gurunya dan golongannya disebut dengan i`tazal (menyendiri/menyimpang) dan ini yang menjadi cikal bakal dari aliran Muktazilah nantinya.
Washil bin Atha’ ini eksis pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan dan khalifah Hisyam bin Abdul Malik, dia juga adalah orang yang sudah terobsesi dengan paham Qadariyah yang dibawa oleh ma’abad al-Juhani dan Ghaylan ad-Dimisyqi, yang kemudian Washil bin Atha’ mulai untuk menyuarakan faham Qadariyah serta mengajak masyarakat pada zaman itu untuk mengikuti pemikirannya[2].
Pemikiran-pemikiran menyimpang Al-wāshîliyah
Secara garis besar, Al-wāshîliyah ini mempunyai empat faham yang menyimpang dari ajaran Ahlusunah wal Jamaah.
Pertama
Menafikan sifat ma’aninya Allah yang berjumlah tujuh, yakni qudrat, iradah, ‘ilmu, hayat, sama’, bashar dan kalam. Mereka menafikan sifat ma’ani berlandaskan argumen bahwa tidak ada dua benda yang mempunyai sifat qodim, argumen ini muncul karena mereka telah terjebak dalam pemahaman bahwa bahwa sifat-sifat Allah ﷻ itu adalah ‘ainud-Dzat (Dzat Allah ﷻ).
Paham demikian tentu sangat fatal sekali, sebab pengertian sifat ma’ani secara etimologi adalah sifat yang dapat diterima oleh Zat Allah ﷻ sama halnya dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Sedangkan secara terminologinya, sifat ma’ani adalah sifat yang menetap pada sifat-sifat yang wajib bagi Allah ﷻ secara hukum. Seperti, bila ada yang mengatakan bahwa Allah ﷻ adalah Zat Yang Mahakuasa (qadiran) maka wajib bagi Allah ﷻ memiliki sifat qudrat. Gampangnya, sifat ma’ani ini bukan ‘ainud-Dzat, tetapi sifat yang menjadi tambahan pada Zat Allah ﷻ (zaidatun ‘ala Zat)[3]. Dari pemahaman ini, jelas bahwa argumen yang telah dibawakan oleh golongan Al-wāshîliyah tentu sangat keliru. Sebab, tidaklah bisa dibenarkan bila Allah ﷻ sebagai Zat yang Maha Kuasa, tanpa mempunyai sifat qudrat. Juga tidak dapat diabsahkan bila Allah ﷻ berkehendak, tetapi tidak bersifat iradat.[4]
Kedua
Washil bin Atha’ mengatakan, dalam masalah qadar mengikuti kepada pemikirannya Ma’bad al-Juhani dan Ghaylan ad-Dimisyqi, yakni Allah adalah tuhan yang adil serta tidak boleh menyandarkan perkara jelek dan zalim kepada Allah, dan Allah pun tidak boleh untuk menghendaki hambanya untuk melakukan sesuatu yang menyalahi kepada perkara yang telah diperintahkannya.
Seorang hamba dibebani sebuah kewajiban dan larangan, apabila dia toat maka akan diberikan pahala kepadanya, namun jika sebaliknya maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Hamba adalah orang yang melakukan perkara baik dan buruk, sedangkan iman, kufur, toat, dan ma’siat hanyalah sebuah majaz yang di sandarkan kepada pekerjaannya hamba. Allah-lah yang telah memastikan semua hal itu.
Washil bin Atha’ juga berpendapat bahwa seorang hamba itu mustahil untuk memikul sebuah khitob syariat yang tidak mungkin ia lakukan, sebab hal itu telah menyalahi konsep dharuri.
Ketiga
Faham “Al-manzilah baina manzilatain”. Penyebab Washil bin Atha’ mempunyai pemikiran seperti ini ialah ketika dia ditanya perihal orang yang melakukan dosa besar, Washil bin Atha’ pun menjawab, bahwa orang yang melakukan dosa besar bukanlah orang mukmin juga bukan orang kafir akan tetapi dia berada di tengah tenga atau yang dikenal dengan Al-manzilah baina manzilatain.
Akan tetapi faham ini dibantah oleh syekh Hasan al-Bashri dengan pernyataannya:
“Iman adalah salah satu ungkapan untuk perkara yang baik, maka ketika perkara baik itu berada pada diri seseorang maka dia dikatakan sebagai mukmin, namun jika sebaliknya maka dia dikatakan sebagai orang fasiq. Orang fasiq ini bukanlah kafir sebab mereka telah melafadzkan 2 syahadat. Tapi andaikan orang fasiq ini melakukan dosa besar kemudian wafat sebelum dia melakukan taubat maka orang yang seperti ini akan kekal dineraka, akan tetapi siksa yang ia terima lebih ringan di bandingkan orang kafir asli, sebab di akhirat itu hanya ada dua tempat yakni surga dan neraka. Tidak ada tempat di antara surga dan neraka.”
Keempat
Pendapat mereka mengenai salah satu dari dua golongan yang berseteru di perang Jamal serta perang Shiffin Mereka menetapkan bahwa salah satu dari dua kelompok sahabat Nabi yang bertikai di perang Jamal sebagai orang fasik yang akan kekal di neraka selama mereka tidak mau bertaubat dan menyesali perbuatannya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dua kebenaran yang wujud dalam satu pertikaian. Pasti ada kelompok yang salah dan yang benar. Selain itu, mereka juga meyakini salah satu di antara dua golongan yang bertikai di antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sebagai orang yang tidak pantas memimpin umat Islam. Oleh karena itu, mereka tidak mendukung salah satu dari keduanya sebagai pemimpin umat Islam.[5]
Tentu hal ini tidak sesuai dengan pendapat Ahlusunah wal-Jamaah yang meyakini para sahabat sebagai orang-orang yang mulia. Karena dari pengajaran para sahabat, ulama terdahulu mempelajari agama Islam. Menuduh para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah sebagai orang fasik berakibat fatal. Padahal, Baginda Nabi Muhammad telah bersabda:
لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي.
“Jangan kalian mencaci para sahabatku. Semoga Allah melaknat orang yang mencaci para sahabatku.”[6](HR. Thabrani)
Itulah beberapa pokok pemikiran dari Muktazilah yang berbasis Al-Washiliyyah. Pada tulisan selanjutnya, kami akan membahas kelompok Muktazilah basis An-Nidzamiyyah.
Aghits Amta Maula | Annajahsidogiri.id
[1] Syekh al-Mubarrid, Al-kamil, hlm. 921
[2] Imam al-Isfirainiy, at-Tabshir fid–Din wa Tamyizil Firqah an-Najiyah anil–Firaq al-Halikin, hlm. 67
[3] Imam Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri, Tuhfatul-Murȋd Syarhu Jauharatit-Tauhȋd, hal. 74
[4] Imam Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri, Syarhȗs-Sanȗsiyah, hlm. 70
[5] Abu Fattah Muhammad Abdul Karim asy-Syahrasytani, al-Milal wan-Nihal, juz 1 hlm. 49
[6] HR. Ath-Thabrani, al-Mu‘jamul-Ausath [4771].