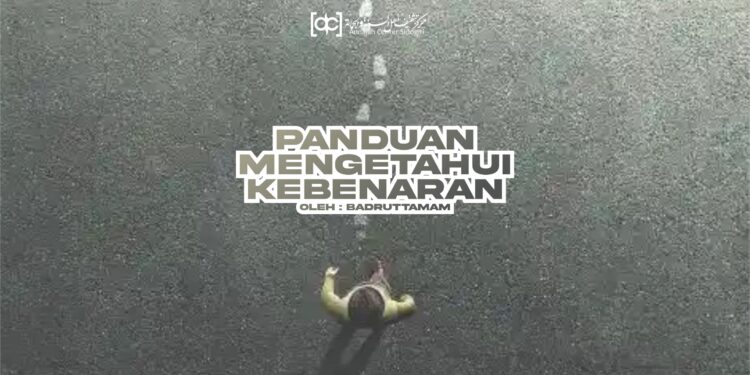Sudah menjadi karakter dasar manusia bahwa ia akan menjadi fanatik terhadap kelompok sendiri dan menganggap kelompok itu yang paling benar. Al-Quran menyatakan:
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ
“Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Q.S. al-Mukminun [23]:53)
Imam Muhammad Abu Zahrah dalam tafsirnya mengatakan, “Setiap kelompok akan menjadi fanatik dan berbahagia atas kelompok sendiri. Mereka menganggap dirinya dalam kebenaran, padahal bisa jadi mereka ada dalam kesesatan. Mendukung (dengan berlebihan) satu pemikiran akan menyebabkan fanatisme. Fanatisme menyebabkan tuli dan buta (terhadap kebenaran).” (Zahratut-Tafâsîr, hlm. 5084)
Fenomena semacam ini sudah cukup sering terjadi. Hanya karena berbeda pendapat, kelompok lain menjadi seperti tidak memiliki kebenaran sama sekali.
Harusnya, untuk menentukan benar atau salah, kita harus melihat menggunakan penilaian yang jernih dan sesuai. Dalam konteks kajian fikih, kebenaran harus sesuai dengan empat dasar penetapan syariat, atau yang sering disebut mashâdirut-tasyrî’, yakni al-Quran, hadis, qiyas dan ijma (Syarîatullah al-Khâlidah, hlm. 12). Dalam konteks kajian akidah, kebenaran harus berdasarkan al-Quran, hadis mutawatir, ijma, dan akal. Qiyas tidak dipakai dalam kajian akidah (Dînuka fî Khatr, hlm. 07).
Perilaku dan Perkataan Bukan Dalil
Tidak berbeda dari kelompok, kebenaran juga tidak bisa dinilai dari tokoh. Hanya karena tokoh A yang mengatakan atau melakukan, misalnya, bukan berarti itu pasti benar. Musa bin Abdil-A’la as-Sadafi bercerita, suatu hari beliau mengatakan kepada Imam asy-Syafii, “Laits pernah berkata, jika kamu melihat seseorang berjalan di atas air, maka jangan sampai tertipu olehnya, hingga dia terbukti berpegang teguh kepada al-Quran.” Imam asy-Syafii lantas menjawab, “Penjelasan Laits masih kurang. Bahkan jika kamu melihat seseorang berjalan di atas air, sekaligus bisa terbang di atas langit, maka jangan pernah sampai tertipu, hingga terbukti bahwa dia berpegang teguh kepada al-Quran” (Syarhuth-Thahâwiyah fîl-Aqîdah al-Islâmiyah, hlm. 533).
Imam al-Ghazali mengecap orang-orang yang menilai kebenaran dari satu tokoh sebagai orang yang malas berpikir (dhua’afâil-uqul). Orang yang mau berpikir, kata beliau, harusnya mengikuti Sayidul-Uqalâ’ (Pemimpin Orang-orang yang Berakal), Sayidina Ali. Sayidina Ali pernah berkata:
لاَ تَعْرِفِ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ، إِعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ اَهْلَهُ
“Jangan sekali-kali mengukur kebenaran dari tokoh. Kenali kebenaran itu sendiri, niscaya kamu akan tahu siapa pemangku kebenaran sebenarnya.”
Bagi Imam al-Ghazali, kebenaran harus dilihat dari perkataan atau pekerjaan dulu. Bila memang benar, maka perkataan atau perbuatan itu bisa diterima. Walaupun misalnya, perkataan atau perbuatan itu datang dari orang yang tidak disukai. (al-Munqidh minadh-Dhalâlah, hlm. 74)
Dari keterangan tadi, kita tahu bahwa dalam menentukan kebenaran ada urutannya. Urutan yang benar adalah, kita tahu hakikat dari kebenaran terlebih dahulu, baru kita tahu siapa yang memang benar atau salah. Bukan malah sebaliknya.
Terakhir, kami ingin mengutip dawuh salah satu guru kami, Mas Muhammad Jibril bin Kiai Nawawy Sadoellah. Dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan, “Kebenaran itu ‘apa’, bukan ‘siapa’” (Nab’ul-Hikam).
Badruttamam | Tauiyah